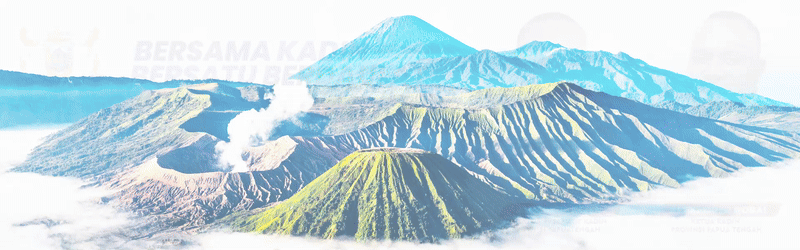
 Foto Keiya Albertus,S,Sos
Foto Keiya Albertus,S,SosWarga Boven Digoel, Papua Selatan, turun ke jalan. Mereka membawa poster, spanduk, dan simbol adat. Bukan untuk menuntut uang, bukan pula untuk politik, tetapi untuk memprotes cara pemusnahan mahkota burung Cenderawasih—simbol kebanggaan orang asli Papua—yang dilakukan oleh Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Papua dengan cara dibakar.
Bagi masyarakat adat, pembakaran ini bukan sekadar pemusnahan barang sitaan. Ini adalah pembakaran harga diri, pembakaran identitas yang selama berabad-abad dijaga sebagai lambang martabat dan spiritualitas.
Mereka menilai tindakan tersebut tidak patut dilakukan. Mahkota burung Cenderawasih bukan benda biasa. Ia digunakan dalam upacara adat, penobatan, pesta perdamaian, dan penyambutan tamu terhormat. Ia adalah mahkota kebudayaan, bukan komoditas.
Di tengah gelombang protes itu, Bupati Boven Digoel, Roni Omba, mengimbau warganya untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan anarkistis. Ia meminta masyarakat menyalurkan aspirasi dengan damai, agar suara Papua tetap bermartabat di hadapan bangsa.
Namun di sisi lain, Intelektual Mee Pago, Albertus Keiya, menyampaikan suara yang lebih dalam dari sekadar amarah. Ia bicara tentang rasa kemanusiaan yang terluka, tentang simbol yang seharusnya dihormati, dan tentang cara berpikir negara yang masih gagal memahami hati orang Papua.
Bagi masyarakat adat Papua, burung Cenderawasih bukan hanya satwa. Ia adalah roh yang turun dari surga, tanda kedamaian, keindahan, dan kemuliaan. Mahkota yang dibuat dari bulu burung ini menjadi simbol kebesaran dan keluhuran jiwa manusia Papua.
Sejak ratusan tahun lalu, mahkota ini diwariskan dari generasi ke generasi. Hanya orang-orang tertentu yang berhak mengenakannya dalam upacara adat yang sakral. Ketika mahkota itu dibakar, maka sesungguhnya yang hangus bukan hanya bulu, tetapi sejarah dan martabat manusia.
Albertus Keiya, tokoh intelektual Mee Pago, menyampaikan keprihatinannya dengan nada tegas namun penuh kebijaksanaan:
“Kalian boleh bicara hukum, kalian boleh bicara aturan, tapi kalian tidak bisa membenarkan pembakaran simbol adat. Itu bukan penegakan hukum, itu penistaan budaya! Negara yang beradab tidak membakar simbol kebanggaan bangsanya sendiri.”
Peristiwa itu bermula ketika video pemusnahan mahkota burung Cenderawasih oleh BBKSDA Papua di halaman kantor mereka di Kota Jayapura beredar di media sosial. Dalam video itu terlihat api membakar beberapa mahkota yang disebut sebagai hasil sitaan dari patroli dan pengawasan terhadap perdagangan satwa liar ilegal.
Tindakan ini sontak memicu reaksi keras. Warga menilai cara tersebut tidak manusiawi dan tidak menghormati nilai budaya Papua.
Majelis Rakyat Papua Selatan (MRPS) bahkan menyampaikan keprihatinan dan menegaskan bahwa masih ada cara lain yang lebih bermartabat untuk menegakkan hukum tanpa harus membakar simbol adat.
Mereka mengusulkan agar benda-benda hasil sitaan seperti itu diserahkan kepada lembaga adat, museum budaya, atau universitas sebagai sarana edukasi dan pelestarian nilai budaya. Dengan begitu, penegakan hukum tetap berjalan, tanpa harus melukai batin rakyat.

sedang bakar mahkota cenderawasih papaua
Setelah gelombang reaksi keras di berbagai daerah, Kepala BBKSDA Papua, Johny Santoso Silaban, akhirnya menyampaikan permintaan maaf secara terbuka.
Ia mengakui bahwa tindakan pemusnahan dengan cara dibakar telah menimbulkan ketersinggungan dan kemarahan publik, terutama masyarakat adat Papua.
Dalam pernyataannya, BBKSDA Papua menegaskan bahwa langkah pemusnahan dilakukan semata-mata untuk menegakkan hukum dan memutus rantai perdagangan ilegal satwa liar, bukan untuk melecehkan nilai budaya masyarakat Papua.
Albertus Keiya menanggapi permintaan maaf itu dengan bijak namun tegas:
“Saya menghargai permintaan maaf yang disampaikan. Tapi mari saya katakan terus terang: Anda salah. Pembakaran simbol adat tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun. Bila perlu, buatlah Peraturan Daerah (Perda) untuk mengatur dan melindungi simbol adat, bukan malah membakarnya. Jangan main api di tanah yang penuh dengan luka.”
Keiya menilai bahwa permintaan maaf hanyalah langkah awal. Yang dibutuhkan bukan sekadar ucapan, tetapi perubahan sistemik dalam cara pandang negara terhadap adat dan manusia Papua.
Warga Boven Digoel marah, tetapi mereka tahu batasnya. Mereka menggelar aksi dengan damai, membawa pesan yang kuat namun santun: “Hargai simbol kami, hormati budaya kami.”
Bagi mereka, pembakaran mahkota itu ibarat menyiram bensin ke luka lama—luka tentang ketidakadilan, diskriminasi, dan perlakuan yang merendahkan.
“Kami sudah terlalu lama diam. Sekarang kami hanya ingin keadilan. Jangan terus ajari kami cara mencintai Indonesia, tapi kalian sendiri membakar lambang kami yang paling suci,” ucap seorang warga dalam aksi di Tanah Merah, Boven Digoel.
Keiya menilai bahwa protes masyarakat adalah wujud kesadaran budaya dan kemanusiaan yang sehat, bukan bentuk perlawanan terhadap hukum. Ia menegaskan, orang Papua bukan anti-konservasi, bukan anti-pemerintah, tetapi menolak tindakan tidak manusiawi atas nama penegakan hukum.
Keiya menegaskan kembali posisi masyarakat Papua: mereka menghormati hukum, tetapi hukum harus dijalankan dengan hati dan kebijaksanaan.
“Kita tidak menolak konservasi, tapi kita menolak cara yang salah. Kalau ingin melindungi burung Cenderawasih, lindungi juga manusia Papua yang menjaga hutan tempat burung itu hidup. Jangan hanya hukum yang bicara, tapi biarkan hati juga bicara.”
Ia menyampaikan bahwa tidak ada satu pun orang Papua yang ingin burung Cenderawasih punah. Mereka mencintai satwa itu seperti mencintai dirinya sendiri. Yang membuat mereka marah adalah cara yang merendahkan simbol suci yang sudah menjadi bagian dari kehidupan adat sejak ratusan tahun.
“Seandainya barang-barang itu disita, lalu diserahkan ke museum atau lembaga adat, tidak akan ada masalah sebesar ini. Tapi ketika kalian membakar, kalian membakar perasaan seluruh rakyat Papua.”
Di balik peristiwa ini, Albertus Keiya melihat masalah yang lebih besar: cara negara memandang orang Papua masih keliru.
Papua sering diperlakukan bukan sebagai saudara sejajar, melainkan sebagai objek kebijakan.
“Yang harus diperbaiki bukan orang Papua, tetapi sistem dan cara pandang negara terhadap orang Papua. Orang Papua sudah hidup ratusan tahun dengan budaya dan adatnya sendiri. Jangan lagi tunjukkan stereotip yang menyakitkan, karena setiap tindakan yang salah atas nama hukum akan melahirkan luka baru di hati kami.”
Keiya menilai bahwa bangsa yang benar-benar besar adalah bangsa yang tahu cara menghormati budaya semua anak bangsanya.
Kekayaan Indonesia bukan hanya sumber daya alamnya, tetapi keragaman nilai-nilai budaya dari Sabang sampai Merauke.
Keiya juga mengungkapkan kecurigaan yang muncul di tengah masyarakat: apakah tindakan seperti ini sengaja dilakukan untuk menguji reaksi orang Papua?
“Saya mulai curiga, jangan-jangan cara berpikir orang Papua sedang dijadikan bahan uji coba. Kalau viral, baru minta maaf. Kalau tidak, dibiarkan begitu saja. Atau sengaja biarkan kami marah sendiri agar perhatian kami teralihkan dari hal-hal yang lebih penting.”
Ia menggambarkan situasi ini seperti penjara tak terlihat, di mana orang Papua merasa terus diawasi, diatur, dan disalahpahami, tanpa ruang untuk menunjukkan martabat dan jati dirinya.
“Kasihan sekali nasib orang Papua. Seperti hidup dalam penjara yang tak terlihat oleh mata kepala, tapi sangat terasa oleh mata batin.”
Albertus Keiya lalu menyoroti akar persoalan yang lebih luas: eksploitasi sumber daya alam yang terus terjadi tanpa memberi kesejahteraan bagi rakyat Papua.
“Kalian jadikan Tanah Papua seperti ATM Jakarta—diambil hasilnya, dihisap kekayaannya, tapi ketika harga diri kami diinjak, kalian diam.”
Papua telah memberi emas, gas, kayu, dan tanah subur untuk Indonesia, tapi yang diterima sering kali hanyalah janji dan stigma.
Menurut Keiya, selama sistem masih timpang, selama manusia Papua belum diakui secara bermartabat, maka perdamaian hanya akan jadi kata tanpa makna.
Sebagai langkah konstruktif, Keiya mendorong lahirnya Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Simbol dan Warisan Budaya Papua.
Ia menilai Perda ini penting agar lembaga pemerintah tidak lagi bertindak tanpa mempertimbangkan nilai adat dan etika lokal.
“Bila perlu, engkau buatkan Perda. Peraturan daerah yang jelas, tegas, dan berpihak pada penghormatan terhadap simbol adat. Jangan main bakar! Jangan mempermalukan budaya bangsa sendiri dengan alasan penegakan hukum.”
Ia menambahkan, jika negara serius menjaga konservasi, maka langkah pertama adalah melibatkan masyarakat adat sebagai penjaga utama alam Papua, bukan memperlakukan mereka sebagai pelaku ilegal.
Meski kecewa, Keiya menolak menyerah pada kebencian. Ia percaya Papua masih bisa berdamai jika semua pihak mau belajar dari kesalahan ini.
“Kami tidak menolak pembangunan. Kami hanya menolak penghinaan. Kami tidak menolak hukum. Kami hanya menolak cara yang tidak manusiawi. Kami tidak menolak konservasi. Kami hanya ingin dihormati sebagai manusia.”
Keiya juga mengajak generasi muda Papua untuk terus menjaga budaya dan hutan mereka dengan pengetahuan dan cinta, bukan dengan kemarahan.
“Burung Cenderawasih boleh kalian bakar, tapi semangat orang Papua tidak akan pernah padam. Kami tetap berdiri dengan kepala tegak, karena kami tahu Tuhan belum meninggalkan kami.”
Peristiwa pembakaran mahkota Cenderawasih telah membuka mata bangsa ini tentang pentingnya menghormati budaya daerah dan nilai kemanusiaan.
Permintaan maaf Kepala BBKSDA Papua, Johny Santoso Silaban, adalah langkah awal yang baik, tapi belum cukup. Luka ini butuh penyembuhan melalui kebijakan nyata, bukan kata-kata.
Albertus Keiya mengingatkan dengan penuh kebijaksanaan:
“Bangsa yang beradab adalah bangsa yang bisa belajar dari kesalahan, bukan yang menutupinya dengan alasan hukum. Jangan lagi ada api yang membakar simbol-simbol suci kami. Jadikan peristiwa ini pelajaran untuk semua—bahwa hukum tanpa hati akan selalu melahirkan luka baru.”
Dari lembah Mee Pago, dari tanah Boven Digoel, dari hati rakyat Papua yang tulus, satu suara menggema:
Hargai kami, dengarkan kami, dan jangan lagi bakar simbol kami.
Ditulis oleh:
Albertus Keiya, S.Sos
Intelektual Mee Pago – Pemerhati Kemanusiaan dan Budaya Papua
Sumber referensi:
- Kompastv.com — “Warga Boven Digoel Protes Pembakaran Mahkota Burung Cenderawasih oleh BBKSDA Papua”
-
DetikSulsel — “BBKSDA Papua Minta Maaf Pembakaran Mahkota Cenderawasih Picu Demo Rusuh”



















Tidak ada komentar